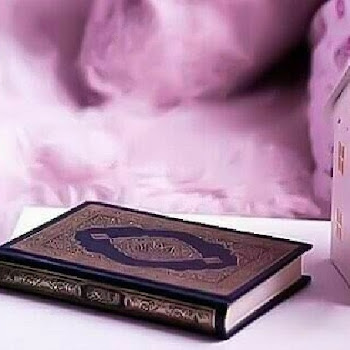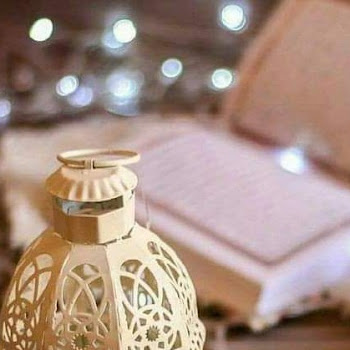Sigit Suhandoyo
A. PENDAHULUAN
Diutusnya Nabi Muhammad saw menandai permulaan perubahan besar dalam peradaban manusia akhir zaman. Sejak turunnya wahyu pertama --permulaan surat al-‘Alaq(1) --, agama Islam telah menyerukan pembebasan akal dari belenggu-belenggu khurafat, taqlid dan kebekuan proses berfikir. Abul Hasan an Nadawi mengemukakan,
و قد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة، و لا ذوا إلى الأديرة و الكنائس و الخلوات، فرارا بدينهم من الفتن وضناً بأنفسهم، أو رغبة إلى الدعة و السكون، و فراراً من تكاليف الحياة و جدها، أو فشلاً في كفاح الدين و السياسة و الروح و المادة، و من بقى منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك و أهل الدنيا، و عاونهم على إثمهم و عدوانهم، و أكل أموال الناس بالباطل(2)
Dalam pengertian lain an-Nadawi menggambarkan bahwa pada masa sebelum diutusnya nabi Muhammad saw, sebagian pemuka agama mengasingkan diri dari kehidupan sosial, bersembunyi dalam tempat-tempat ibadah dan sebagainya untuk menjauhkan iman mereka dari gangguan dan penindasan. Mereka mengasingkan diri karena merasa apatis terhadap diri mereka sendiri, mencari ketenangan dengan melarikan diri dari tugas-tugas hidup, ataupun karena merasa gagal berjuang dalam agama, politik, kehidupan spiritual maupun materi. Sedangkan sebagian lain yang ingin hidup senang, bergaul dengan kelas borjuis dan bekerjasama dengan para penguasa tersebut dalam kejahatan, kezaliman dan memakan harta dengan cara yang batil.
Kemudian turunlah wahyu pertama kepada Nabi Muhammad saw melalui perintah “bacalah!” Perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk membaca namun tidak disertai teks, memberikan makna yang sangat luas.
Ibnu ‘Asyūr mengemukakan pendapat bahwa, perintah ini merupakan isyarat bagi ummat Muhammad saw agar membaca, menulis dan berilmu pengetahuan. Talqīn (bimbingan) Jibril kepada Nabi Muhammad saw memberikan arti otoritas keilmuan serta motivasi akan mudahnya penguasaan terhadap ilmu.(3) Demikian pula pendapat Az-Zuhaylī, ayat-ayat ini merupakan perintah belajar membaca dan menulis karena itu adalah sarana bagi penguasaan agama dan dunia, dasar bagi tegaknya ilmu pengetahuan dan moral estetika, serta terbinanya kebudayaan dan peradaban ummat Islam.(4) Tema tarbiyyah pada ayat-ayat yang mula diturunkan ini menurut al-Biqā’ī menegaskan makna bahwa al-Qur’an adalah kumpulan seluruh kebaikan dunia dan akhirat yang kemudian Allah jadikan Rasulullah saw fasih dengannya. Ketentuan ini merupakan karunia bagi seluruh ummat manusia karena Allah mendidik Rasul dengan sebaik baik pendidikan serta mengajarnya dengan sebaik-baik pengajaran.(5) Hingga Muhammad Abduh menuliskan,
“و إن لم يسترشدوا بفاتحة هذا المكتاب المبين و لم يستضيئوا بهذا لبضياء الساطع فلا أرشدهم الله أبدا”(6).
Seandainya ayat-ayat pembukaan wahyu ini tidak menggetarkan, menggugah semangat ummat Islam, niscaya tidaklah mereka akan bangkit lagi (mencapai kejayaan) selama-lamanya. Hingga pada saatnya gerakan yang dipelopori seorang nabi yang ummi dan sekelompok kecil sahabatnya yang miskin dan tertindas pada masa itu berhasil mencatatkan kegemilangan pembangunan peradaban dunia modern dan dinaungi oleh nilai-nilai spiritual. Keberhasilan yang tak lepas dari peran Nabi mendidik para sahabatnya ini memberikan argumen akan urgensi pendidikan bagi manusia. Pendidikan selain sebagai sebuah kewajiban syari’at, juga merupakan kebutuhan individu dan tuntutan sosial.
B. PEMBAHASAN
1. Pendidikan Merupakan Kewajiban Agama
Pendidikan merupakan kewajiban yang disyari’atkan. Kewajiban ini tertera dalam perintah Allah kepada orang-orang beriman agar tidak mengabaikan belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan meskipun ada perintah berjihad,
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (at taubah 122)
Kewajiban memperdalam pengetahuan dalam ayat ini menurut al-Syafi’i bersifat kifayah.(7) Meski demikian, sejajarnya perintah jihad perang dan pendidikan dalam ayat ini menjelaskan akan tegasnya misi Islam dalam hal penyebaran pengetahuan mengiringi penaklukan wilayah. Hal ini menunjukkan, kebutuhan suatu bangsa terhadap jihad dan para mujahid sama seperti kebutuhan terhadap ilmu dan para ulama.(8) Menurut Ibnu ‘Asyūr penyebaran keilmuan, etika Islam dan mencerdaskan akal fikiran adalah manifestasi dari tujuan Islam dalam pengelolaan ummat berdasarkan agama dan penjagaan agama dengan kekuatan ummat.(9)
Wajibnya pendidikan juga tertera dalam hadits perintah menuntut ilmu serta mengajarkannya. Dari Anas bin Mālik ra, Rasulullah saw telah bersabda,
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ(10).
“Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan (mengajarkan) ilmu kepada orang yang bukan ahlinya ibarat orang yang mengalungkan beberapa ekor babi dengan mutiara, permata dan emas.”
Ḫadīṡ ini merupakan perintah agar setiap muslim yang balig dan berakal membebaskan dirinya dari kebodohan. Para ulama ḥadīṡ berbeda pendapat tentang tingkatannya, antara farḍu ‘ain dengan farḍu kifāyah. Sebagian berpendapat ilmu agama dengan ilmu keduniaan. Adapula yang berpendapat ‘ilmu ikhlāṣ merupakan farḍu ‘ain, demikian pula ada yang berpendapat ilmu tauḥīd merupakan farḍu ‘ain, dsb.(11) Pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya bersumber pada pemikiran bahwa setiap muslim selain harus memiliki keilmuan yang memadai bagi dirinya untuk beribadah kepada Allah, juga memiliki spesialisasi keilmuan tertentu yang mendalam.
Ḥadīṡ ini juga berisi perintah agar orang-orang berilmu mengajarkan ilmunya kepada ahli ilmu. Para ulama ḥadīṡ berbeda pendapat tentang ahli ilmu yang dimaksudkan, ada yang berpendapat orang yang memiliki kecenderungan terhadap ilmu, memiliki kefahaman, menuntut ilmu bukan untuk sekedar tujuan dunia, menuntut ilmu karena Allah, dsb.(12) Dengan demikian para pendidik berkewajiban untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didiknya, mengembangkan bakat, memberikan kefahaman serta menjadikan keikhlasan sebagai landasan atas segala amaliahnya.
Kewajiban pendidikan juga tertera dalam surat al Baqarah ayat 159 tentang larangan menyembunyikan ilmu,
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati,”
Menurut Ibnu ‘Āsyūr pengertian “البينات” dalam ayat ini adalah pokok-pokok syari’ah yang menjadi landasan atas berbagai hukum dalam kehidupan manusia termasuk perkara aqidah, fiqh maupun etika. Sedangkan pengertian “الهدى” adalah penerangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi kemashalatan individu dan masyarakat.(13) Serupa dengan pendapat tersebut, menurut az-Zuhailī, Ilmu-ilmu yang dilarang untuk disembunyikan dalam ayat ini bermakna umum, bisa berupa hukum syari’ah, ilmu yang bermanfaat maupun ide-ide, pandangan, gagasan serta solusi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat.(14) Selanjutnya menurut Ibnu ‘Āsyūr ayat ini menunjukkan argumen akan wajibnya penjagaan terhadap ilmu, pendidikan, pengajaran dan penyebarluasan pengetahuan.(15) Seorang berilmu yang dengan sengaja bermaksud menyembunyikan pengetahuannya kepada masyarakat sungguh telah berbuat dosa.(16)
Firman Allah tersebut di atas sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 174 berikut,
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.”
Larangan menyembunyikan ilmu pengetahuan juga dijelaskan dalam beberapa riwayat hadits. Dari Abdullah bin ‘Amr ra, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda,
مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.(17)
“Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api pada hari kiamat.”
Demikian pula hadits dari Abu Sa’id al Khudry ra, Rasulullah saw telah bersabda,
مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ أَمْرِ الدِّينِ، أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ.(18)
“Barang-siapa yang menyembunyikan ilmu yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadanya dalam perkara manusia dan agama, kelak Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api pada hari kiamat.
2. Pendidikan Merupakan Kebutuhan Manusia
Meskipun manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk dengan berbagai potensi akal, fisik, indera, nafsu dan hati namun manusia terlahir dalam keadaan lemah. Dengan demikian manusia membutuhkan pengasuhan dan pendidikan bagi dirinya guna mengembangkan dan mengarahkan potensi-potensi tersebut. Allah ta’ala berfirman dalam surat an-nahl ayat 78,
“والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون”
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”
Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia terlahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, kemudian Allah memberikan manusia berbagai perangkat yang akan menyampaikannya kepada ilmu pengetahuan.(19) Manusia diciptakan dengan potensi akal yang dapat berkembang dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Melalui hal tersebut akal manusia dapat berfikir, berpendapat, mendefinisikan sesuatu serta membangun pengetahuan.(20) Demikianlah pendidikan dibutuhkan oleh manusia dikarenakan manusia memiliki kepribadian yang unik, memiliki tingkah laku, memiliki kecerdasan dan daya pikir, serta memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kepribadian.
Sebagai mahluk psikologis manusia pada hakikatnya merupakan mahluk yang berfikir, merasa dan berkehendak serta menciptakan dinamisme. Selain terkait pengembangan berbagai potensi, menurut al-Maraghi manusia membutuhkan pendidikan untuk memahami sesuatu dengan mendalam, menimbang antara kebaikan dan keburukan serta menimbang antara petunjuk dan kesesatan.(21) Dalam sebuah riwayat hadits qudsi dari ‘Iyadh bin Himar ra, pada khutbahnya Rasulullah saw menyampaikan,
وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ(22)
“Sesungguh Aku (Allah) menciptakan hamba-Ku seluruhnya hanif (berada dalam kebaikan), kemudian datang kepada mereka syaitan yang memalingkan mereka dari agama ”
Menurut Ibnu Abdil Bar, Allah telah menciptakan manusia seluruhnya hanif, yaitu muslim, bersaksi akan keesaan Allah dan menghadapkan dirinya dalam ketundukan kepada Allah semata(23) . Kemudian syaitan memalingkan manusia dari kebenaran agama. Menurut an-Nawawi, pertama-tama syaitan menjadikan manusia meremehkan urusan agama kemudian menjauhkannya, hingga akhirnya manusia menyingkirkan agama dari kehidupannya. Kemudian Syaitan menjadikan manusia terpikat dengan keburukan yang mengasikkan baginya.(24) Keberhasilan syaitan memalingkan manusia dari kebenaran adalah dikarenakan ia datang kepada manusia dengan “الوسوسة”(25) hasutan, godaan dan ajakan yang bersifat halus yang dibisikkan kedalam hati manusia.
Pendidikan juga dibutuhkan agar manusia dapat mengambil keputusan dengan benar. Diriwayatkan dari Abu Malik a-Asy’ari ra, bahwasanya Rasulullah saw bersaba,
كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا(26)
“Setiap manusia berbuat, maka ada manusia yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya adapula yang membinasakannya.”
Menurut an-nawawi hadits ini menerangkan bahwa, setiap manusia berbuat atas kehendak dirinya dan diantara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah melalui keta’atannya dan memerdekakan dirinya dari siksaan. Dan diantara mereka pula ada yang menjual dirinya kepada syaitan dan nafsunya dan hal tersebut mencelakakannya.(27)
3.Pendidikan Merupakan Kebutuhan Sosial
Pendidikan adalah kebutuhan masyarakat. Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,
مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا.(28)
“Perumpamaan orang-orang yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang terperosok di dalamnya adalah laksana orang-orang yang membagi tempat dalam suatu bahtera, sebagian orang diatasnya dan sebagian dibawahnya. ketika orang-orang yang berada dibawah memerlukan air, tentu mereka harus melintasi orang-orang yang dibagian atas. kemudian mereka berkata, “kami akan lubangi saja bagian bawah ini.” jika mereka membiarkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang dibagian bawah, niscaya akan binasalah semua. Namun bila mereka mencegah perbuatan tersebut, maka akan selamat dan selamatlah semuanya”
Melalui hadits ini Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memberikan sebuah perumpaan yang indah tentang pendidikan sebagai sebuah kebutuhan sosial. Sebab sebuah kesalahan sebagian pihak tidak hanya berdampak negatif pada lingkup individu semata melainkan juga pada lingkup sosial yang lebih luas. Terlaksananya tugas pendidikan bagi masyarakat berbanding lurus dengan keselamatan dan eksistensi masyarakat tersebut.
Sebagai kebutuhan social, pendidikan juga merupakan sarana bagi membangkitkan kemuliaan dan menjaga keselamatan masyarakat.Diriwayatkan dari Tsauban ra bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda,
يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا» ، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ» ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»(29)
“Nyaris sudah bangsa-bangsa (selain Islam) bersekongkol menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana makanannya.” Lalu bertanya seseorang, “Apakah kami pada saat itu sedikit?” Beliau menjawab, “Tidak, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian itu buih seperti buih banjir, dan Allah akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan menimpakan ke dalam hati-hati kalian wahn (kelemahan).” Maka seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah wahn itu?”. Kata beliau, “Cinta dunia dan takut mati.”
Menurut al-Qari, pengibaratan ummat Islam bagaikan buih adalah dikarenakan, Kondisi ummat Islam yang berpecah belah, lemah kemauan, malas berfikir dan tak punya cita-cita yang kokoh.(30) Makna kata wahn dalam hadits di atas adalah “الضَّعْف” atau lemah, sehingga pertanyaan para sabahat adalah, “apakah yang menyebabkan kelemahan (wahn) ummat Islam pada masa itu?”
Nilai penting hadits ini adalah sebagai peringatan agar ummat Islam memperhatikan pendidikan bagi kemajuan dan keselamatan ummat Islam. Sebagaimana perkataan al Qaradhawi,
الدولة القومية لن تستعيد قوتها، مالم تستعد الأمة ذاتها قوتها. فإنها قوة الدولة بقوة شعوبها، فالشعوب الميتة لا تقيم دولة حية، و الشعوب الضعيفة لا تبني دولة قوية، كما في الأثر المشهور "كما تكونوا يولّ عليكم"(31)
Sebuah bangsa tidak dapat mengembalikan kekuatannya selama rakyatnya sendiri tidak mengembalikannya. Kekuatan sebuah bangsa terletak pada kekuatan rakyat. Rakyat yang mati tidak bisa menghidupkan bangsa. Rakyat yang lemah tidak bisa menguatkan bangsa, sebagaimana sebuah pepatah, “sebagaimana adanya kalian begitulah kuasa kalian”.
C. KESIMPULAN
Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan sebuah kewajiban syari’at, Allah mewajibkan aktifitas belajar mengajar sebagaimana Ia wajibkan berjihad menegakkan agama-Nya. Demikian pula perintah menuntut ilmu dan larangan menyembunyikannya bagi kemaslahatan bersama. Selain perintah syari’at, pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Pendidikan merupakan sarana pengembangan pribadi dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan dunia dan akhirat.
Catatan Kaki
- Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah ra, bahwa wahyu yang pertama ditunjukkan kepada Nabi saw adalah ru’ya shadiqah (mimpi yang benar) datangnya malaikat kepada beliau dan membacakan 5 ayat awal surat al Alaq. Lihat Al Bukhari : Shahih al Bukhari, Daar Thuwaiq an Najah, 1422 H, Juz 1, hlm 7 Lihat pula Muslim : Shahih Muslim, Beirut: Daar Ihya at Turats al ‘Arabi, tt, Juz 1, hlm 139.
- Abu al-Hasan al-Nadawi, Mādza Khasir al -Alam bi Inkhithāt al-Muslimīn, (Mesir: Maktabah al Imān, tth), hlm 29.
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, al-Tahrîr wa al-Tanwîr, (Tunisia: Dâr at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984), Juz 30, hlm 434.
- Wahbah bin Musthofâ az-Zuhaylî, Tafsir al-Munîr, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 1418 H), Juz 30, hlm 319.
- Burhânuddîn al-Biqâ’î, Nadzmu ad-Durar, (Cairo: Dâr al-Kitâb al-Islâmî, tt), Juz 22, hlm 152-153.
- Muhammad Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Karim Juz ‘amma,( Mesir : Mathba’atu Mishr, 1341 H), hlm 124.
- Muhammad bin Idris al-Syāfi’ī, Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī, (Saudi Arabia: Dar al-Tadmiriyah, cet. pertama 1427 H), Juz 2, hlm 962. Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh al-Qurthubī dari kalangan Malikiyah. Lihat Syamsuddîn al Qurthûbî, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an, (Cairo: Dâr al Kutub al Mishriyah, 1384 H), Juz 8, hlm 294.
- Anwar al-Baz, al-Tafsīr al-Tarbawī lil Qur’an al Karīm, (Cairo: Dār an Nashr lil Jami’at, 2007) Juz1, hlm 618.
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, op.cit, Juz 11, hlm 59.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dār ihyā`u al-Kutub al-‘Arabiyah, tth), Juz 1, hlm 81, no. 224. Menurut al Haiṡami ḥadīṡ ini ḍa’īf, lihat majma’u az-zawā`id Juz 1, hlm 120.
- Lihat Nūruddīn al-Malā ‘ali al-Qāriy, Muraqātu al-Mafātīh, (Beirut: Dār al Fikr, 1422 H), Juz 1, hlm 301. Lihat pula Zainuddīn al Munāwiy, Faiḍul Qadīr, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah, 1356 H), Juz 4, hlm 267.
- Ibid.
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, op.cit, Juz 2, hlm 66-67.
- Wahbah bin Musthofâ az-Zuhaylî, op.cit, , Juz 2, hlm 54.
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, loc.cit,. Lihat juga az-Zuhaylî,Ibid.
- Syamsuddîn al Qurthûbî, op.cit, Juz 2, hlm 185. Lihat juga az-Zuhaylî,Ibid.
- Abu ‘Abdullah al Ḥākim, al Mustadrak ‘ala aṣ-ṣaḥiḥain, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), Juz 1, hlm 182, no 346. ḥadīṡ ini ṣaḥīḥ.
- Ibnu Majah, op.cit, Juz 1, hlm 97, ḥadīṡ no 265. ḥadīṡ ini ḍa’īf.
- Jamāluddīn Ibn al-Jawzī, Zād al-Masīr fī ‘Ilmi at-Tafsīr, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422 H), Juz 2, hlm 575.
- Muhammad Thâhir bin ‘Āsyūr, op.cit, Juz 14, hlm 231.
- Ahmad bin Musthofā al Marāghī, Tafsir al Marāghī, (Mesir : Perusahaan Penerbitan Musthofa al-Halby, 1365 H), Juz 14, hlm 118.
- Muslim bin al Hajjaj Abu al hasan al Qusyairy an Naisabury, Shahih Muslim, (Beirut: Daar ihyau At Turats al Araby, tt ), vol 4, h. 2197, hadits no 2865.
- Lihat Ibnu ‘Abdil Bar, at-Tamhid lima Fil Muwatho,, (Maroko: Kementrian Wakaf, 1387 H), vol 18,hlm 74-76
- Abu Zakaria Muhyiddin Yahya an Nawawi, al Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihyau Turats al ‘Arabiy, 1392 H), vol 17, hlm 197.
- Nūruddīn al-Malā ‘alî al-Qāriy, op.cit, vol 8, hlm 3367.
- Muslim bin al Hajjaj, Op.cit, vol 1, hlm 203, hadits no 223.
- An Nawawi, Op.cit, vol 3, hlm 102.
- Bukhari, Op.cit, vol 3. Hlm 139, hadits no 2493.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Maktabah al ‘Ashriyah, tth), vol 4, hlm 111, hadits no 4297. Shahih menurut al Albani.
- Nuruddin al Qari, Op.cit, vol 8, hlm 3366.
- Yusuf al Qaradhawi,Ummatuna Baina Qarnain, (Beirut: Daar asy Syuruq, 1421 H), hlm 240.